
REFORMULASI FIQH, MEMUNGKINKAN?
Sebagai sistem normatif yang paling normal dari ajaran Islam, fiqh sering direalisir melampaui batas-batas kemampuannya. la dipandang sebagai disiplin yang mewakili, (representatif) keseluruhan cita-cita moral Islam yang tanpa cacat. Tapi dengan anggapan itu, fiqh selalu menjadi sasaran pertama semua kegelisahan dan kekurangpuasan yang memunculkan pertama tanda-tanda di sekitar konsepsi Islam yang sempurna itu.
Akhir-akhir ini, kegelisahan itu muncul terutama dari asumsi bahwa fiqh itu kaku dan tidak kontekstual, khususnya bila dihadapkan pada masalah-masalah kontemporer sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini terbukti dengan cukup banyaknya lontaran-lontaran yang mencoba menggugat atau setidak-tidaknya mempertanyakan kembali relevansi fiqh yang merupakan hasil karya mujtahid (penggali hukum) terdahulu.
“Gugatan terhadap fiqh yang mengimplisitkan pembaharuan fiqh, reformulasi fiqh, mungkinkah itu ?” komentar MA. Fa tah Santosa, mantan direktur Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran, Muhanengawali makalahnya yang berjudul Reformulasi Fiqh: Analisis Metodologi pada diskusi Forum Pengkajian Hukum Islam (FPHI) di Fakultas Ilmu-ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang bertemakan “Menggugat Fiqh, Mencari Alternatif Baru”.
Sedangkan Drs. Zarkasyi A.S, dekan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membawakan makalah dengan judul Fiqh Klasik dan Fiqh Baru menganggap gugatan terhadap fiqh berarti adanya maksud mencari cara yang relevan bagi fiqh untuk mengantisipasi perkembangan permasalahan hukum yang kompleks, akibat perkembangan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara pada globalisasi.
II
Menurut Zarkasyi, pada kepustakaan dikenal dua pengertian fiqh pertama, fiqh dalam pengertian pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at/syara’ yang praktis yang diistinbatkan dari dalil-dalilnya. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara’ yang praktis adalah aturan-aturan yang dijabarkan dari perintah pemberi hukum (syar’i) yang menyangkut masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam berbagai situasi yang konkrit. Kedua, ialah ketentuan ketentuan hukum syara’ itu sen diri. Bila yang pertama merupakan ilmu pengetahuan hukum, maka pengertian yang kedua menunjukkan pada hukum itu sendiri.
Dengan demikian pengertian fiqh yang kedua tidak lain merupakan hasil usaha penjabaran dan mengkongkritkan norma dasar yang bersifat illahi. Yang mana dalam penjabaran ini-yang nantinya akan menghasilkan karya, menurut Fatah Santoso, seorang mujtahid manapun selalu didasarkan pada hal-hal berikut. Pertama, dedikasinya yang tinggi terhadap agama dan perhatiannya kepada kemaslahatan umat demi membumikan pesan-pesan Ilahi. Kedua, Penyusunan dan penggunaan sistem metodologi yang disebut Ushul Fiqh.
Dengan demikian tidaklah berlebihan. kiranya, apabila dikatakan bahwa fiqh mempunyai kekuatan ekspansi logis yang dapat digali untuk mengkongkritkan suatu norma dasar menjawab suatu persoalan hukum yang konkrit. Kekuatan ekspansi fiqh dapat tercermin pada kaidah Alhukmu yaduru ma’a ‘illah. Namun harus tetap diperhatikan walaupun hukum- detail fiqh merupakan hasil penalaran logis dari norma-norma dasar, ekspansinya haruslah didasarkan atas pertimbangan kemanusia-an (kemaslahatan umat).
III
Penulisan fiqh yang dilakukan oleh para fuqoha (baca:mujtahid) klasik, menurut Zarkasyi, nampaknya banyak mengabaikan sistematika sehingga menyulitkan bagi peminat figh untuk memperoleh hukum detail tentang suatu masalah. Jika pun ada, sistematika mujtahid yang satu berbeda dengan mujtahid yang lain. Sistematika kitab fiqh Safi’i, misalnya dimulai dari pembahasan tentang ibadah, muamalah, munakahat, uqubah. Sedangkan Hambali memulainya dengan bab ibadat, jihad, wasiat, albai, warisan, munakahat, uqubah, qodlo, murafa’at. Akibatnya tentu saja mempersulit peminat fiqh untuk mengetahui keragaman pendapat dari mazhab terhadap suatu masalah hukum. Di samping itu, kata beliau selanjutnya, ciri yang jelas dari kitab-kitab fiqh klasik adalah bahwa fuqoha (mujtahid) langsung membahas detail permasalahan tanpa mendahului matannya dengan menggunakan azas-azas hukum yang melandasi detail tersebut.
Fakta yang demikian itu bagi mereka yang belum mendalami fiqh dan yang belajar hanya secara elementer menimbulkan kesan bahwa fiqh tidak mengandung unsur penalaran yang mendalam atau tidak mempunyai aspek penalaran kritis. Hukum-hukum fiqh tidak lain adalah penalaran normatif dari suatu perbuatan atau suatu kenyataan tanpa memiliki struktur penalaran yang logis. Kesan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan kelemahan mina minat untuk mempelajari fiqh, karena tidak membangkitkan daya penalaran.
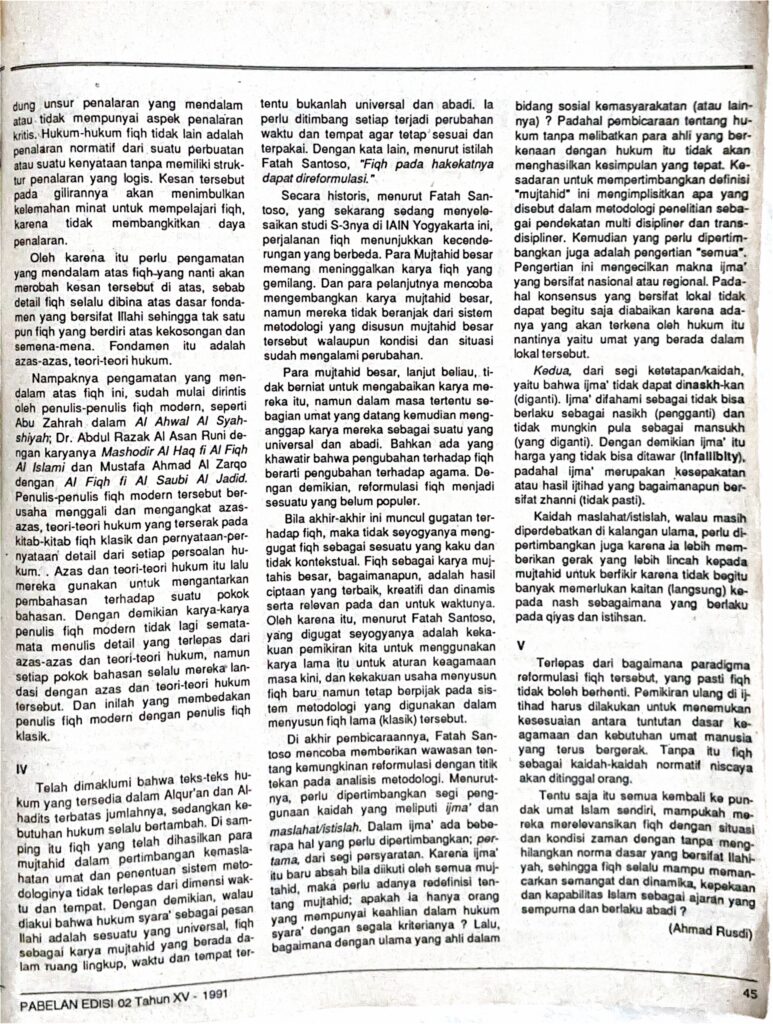
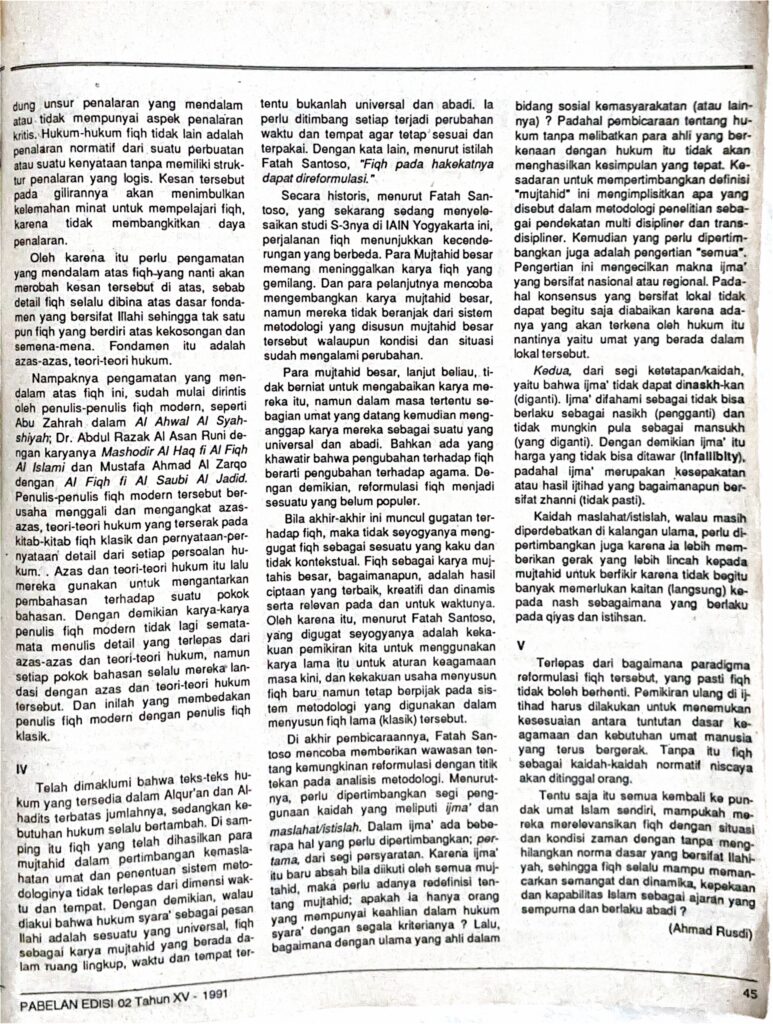
Oleh karena itu perlu pengamatan yang mendalam atas fiqh-yang nanti akan merobah kesan tersebut di atas, sebab detail fiqh selalu dibina atas dasar fonda-men yang bersifat Illahi sehingga tak satu pun fiqh yang berdiri atas atas kekosongan kekosongan dan dan semena-mena. Fondamen itu adalah azas-azas, teori-teori hukum.
Nampaknya pengamatan yang mendalam atas fiqh ini, sudah mulai dirintis oleh penulis-penulis fiqh modern, seperti Abu Zahrah dalam Al Ahwal Al Syah shiyah, Dr. Abdul Razak Al Asan Runi dengan karyanya Mashodir Al Haq fi Al Fiqh Al Islami dan Mustafa Ahmad Al Zarqo dengan Al Fiqh fi Al Saubi Al Jadid, Penulis-penulis fiqh modern tersebut berusaha menggali dan mengangkat azas azas, teori-teori hukum yang terserak pada kitab-kitab fiqh klasik dan pernyataan-pernyataan detail dari setiap persoalan hukum. Azas dan teori-teori hukum itu lalu mereka gunakan untuk mengantarkan pembahasan terhadap suatu pokok bahasan. Dengan demikian karya-karya penulis fiqh modern tidak lagi semata mata menulis detail yang terlepas dari azas-azas dan teori-teori hukum, namun setiap pokok bahasan selalu mereka landasi dengan azas dan teori-teori hukum tersebut. Dan inilah yang membedakan penulis fiqh modern dengan penulis fiqh klasik.
IV
Telah dimaklumi bahwa teks-teks hukum yang tersedia dalam Al-qur’an dan Al-hadits terbatas jumlahnya, sedangkan kebutuhan hukum selalu bertambah. Di sam-ping itu fiqh yang telah dihasilkan para mujtahid dalam pertimbangan kemasla mujtahid da dan penentuan sistem metodologinya tidak terlepas dari dimensi waktu dan tempat. Dengan demikian, walau diakui bahwa hukum syara’ sebagai pesan llahi adalah sesuatu yang universal, fiqh sebagai karya mujtahid yang berada dalam ruang lingkup, waktu dan tempat tertentu bukanlah universal dan abadi. la perlu ditimbang setiap terjadi perubahan waktu dan tempat agar tetap sesuai dan terpakai. Dengan kata lain, menurut istilah Fatah Santoso, “Fiqh pada hakekatnya dapat direformulasi.”
Secara historis, menurut Fatah Santoso, yang sekarang sedang menyelesaikan studi S-3nya di IAIN Yogyakarta ini, perjalanan fiqh menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Para Mujtahid besar memang meninggalkan karya fiqh yang gemilang. Dan para pelanjutnya mencoba mengembangkan karya mujtahid besar, namun mereka tidak beranjak dari sistem metodologi yang disusun mujtahid besar tersebut walaupun kondisi dan situasi sudah mengalami perubahan.
Para mujtahid besar, lanjut beliau, tidak berniat untuk mengabaikan karya mereka itu, namun dalam masa tertentu sebagian umat yang datang kemudian meng-anggap karya mereka sebagai suatu yang universal dan abadi. Bahkan ada yang khawatir bahwa pengubahan terhadap fiqh berarti pengubahan terhadap agama. Dengan demikian, reformulasi fiqh menjadi sesuatu yang belum populer.
Bila akhir-akhir ini muncul gugatan terhadap fiqh, maka tidak seyogyanya meng gugat fiqh sebagai sesuatu yang kaku dan tidak kontekstual. Fiqh sebagai karya muj tahis besar, bagaimanapun, adalah hasil ciptaan yang terbaik, kreatif dan dinamis serta relevan pada dan untuk waktunya. Oleh karena itu, menurut Fatah Santoso, yang digugat seyogyanya adalah kekakuan pemikiran kita untuk menggunakan karya lama itu untuk aturan keagamaan masa kini, dan kekakuan usaha menyusun fiqh baru namun tetap berpijak pada sistem metodologi yang digunakan dalam menyusun fiqh lama (klasik) tersebut.
Di akhir pembicaraannya, Fatah Santoso mencoba memberikan wawasan tentang kemungkinan reformulasi dengan titik tekan pada analisis metodologi. Menurut-nya, perlu dipertimbangkan segi penggunaan kaidah yang meliputi jima’ dan maslahah istislah. Dalam ijma’ ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan; per tama, dari segi persyaratan. Karena ijma itu baru absah bila diikuti oleh semua mujtahid, maka perlu adanya redefinisi tentang mujtahid; apakah ia hanya orang yang mempunyai keahlian dalam hukum syara’ dengan segala kriterianya? Lalu, bagaimana dengan ulama yang ahli dalam bidang sosial kemasyarakatan (atau lainnya)? Padahal pembicaraan tentang hukum tanpa melibatkan para ahli yang berkenaan dengan hukum itu tidak akan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Kesadaran untuk mempertimbangkan definisi “mujtahid” ini mengimplisitkan apa yang disebut dalam metodologi penelitian sebagai pendekatan multidisipliner dan transdisipliner. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah pengertian “semua”. Pengertian ini mengecilkan makna ima yang bersifat nasional atau regional. Pada-hal konsensus yang bersifat lokal tidak. dapat begitu saja diabaikan karena ada-nya yang akan terkena oleh hukum itu nantinya yaitu umat yang berada dalam lokal tersebut.
Kedua, dari segi ketetapan/kaidah, yaitu bahwa ijma’ tidak dapat dinaskh-kan (diganti). Ijma’ difahami sebagai tidak bisa berlaku sebagai nasikh (pengganti) dan tidak mungkin pula sebagai mansukh (yang diganti). Dengan demikian ijma’ itu harga yang tidak bisa ditawar (Infallibity). padahal ijma’ merupakan kesepakatan atau hasil ijtihad yang bagaimanapun bersifat zhanni (tidak pasti).
Kaidah maslahat/istislah, walau masih diperdebatkan di kalangan ulama, perlu di-pertimbangkan juga karena ja lebih memberikan gerak yang lebih lincah kepada mujtahid untuk berfikir karena tidak begitu banyak memerlukan kaitan (langsung) ke-pada nash sebagaimana yang berlaku pada qiyas dan istihsan.
Terlepas dari bagaimana paradigma reformulasi fiqh tersebut, yang pasti fiqh tidak boleh berhenti. Pemikiran ulang di ijtihad harus dilakukan untuk menemukan kesesuaian antara tuntutan dasar keagamaan dan kebutuhan umat manusia yang terus bergerak. Tanpa itu fiqh sebagai kaidah-kaidah normatif niscaya akan ditinggal orang.
Tentu saja itu semua kembali ke pun-dak umat Islam sendiri, mampukah me reka merelevansikan fiqh dengan situasi dan kondisi zaman dengan tanpa hilangkan norma dasar yang bersifaling yah, sehingga figh selalu mampu memah carkan semangat dan dinamika, kepekaan dan kapabilitas Islam sebagai ajaran yang sempurna dan berlaku abadi?
(Ahmad Rusdi)