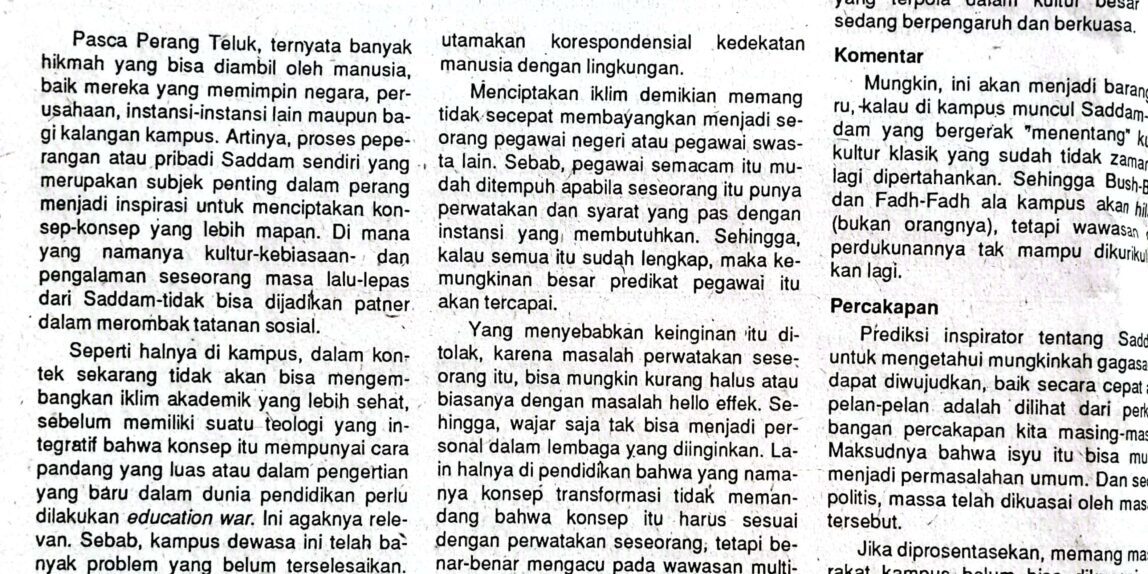
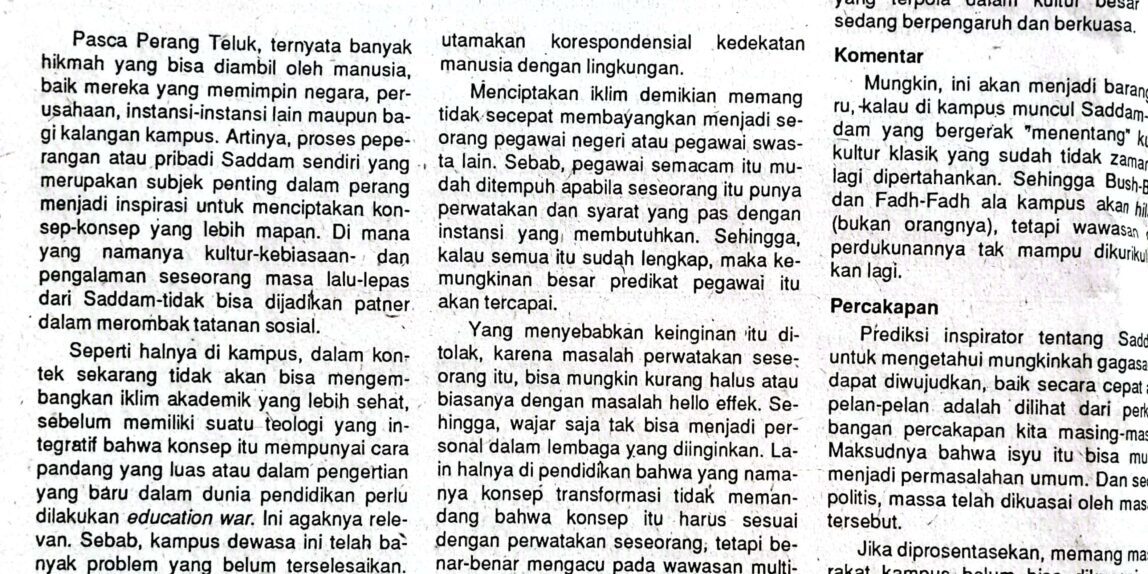
Kampus Perlu “Saddam”
Pasca Perang Teluk, ternyata banyak hikmah yang bisa diambil oleh manusia, baik mereka yang memimpin negara, perusahaan, instansi-instansi lain maupun bagi kalangan kampus. Artinya, proses peperangan atau pribadi Saddam sendiri yang merupakan subjek penting dalam perang menjadi inspirasi untuk menciptakan konsep-konsep yang lebih mapan. Di mana yang namanya kultur kebiasaan dan pengalaman seseorang masa lalu lepas dari Saddam tidak bisa dijadikan patner dalam merombak tatanan sosial.
Seperti halnya di kampus, dalam konteks sekarang tidak akan bisa mengembangkan iklim akademik yang lebih sehat, sebelum memiliki suatu teologi yang integratif bahwa konsep itu mempunyai cara pandang yang luas atau dalam pengertian yang baru dalam dunia pendidikan perlu dilakukan education war. Ini agaknya relevan. Sebab, kampus dewasa ini telah banyak problem yang belum terselesaikan. Misalnya, kesenjangan di berbagai dimensi sosial yang antara lain; kesenjangan transisional, kultural, okupasional dll. Dan masalah ini menurut mantan Deputi Litbang Lipi, Muchtar Buchori harus mendapatkan prioritas untuk dijawab. Pertanyaan kita apakah persoalan tersebut benar-benar menjadi masalah umum?
Jika masyarakat kampus membaca perkembangan pendidikan secara menyeluruh dari masa kemerdekaan hingga periode sekarang maka, pertentangan-pertentangan itu mesti ada dalam benak kita masing-masing. Sehingga, dengan kenyataan itu mobilisasi akademikus akan lebih kuat melihat bahwa kampus memang harus dirombak artinya bukan secara temporal dan personal melainkan dengan sistem menejemen modern yang mengutamakan korespondensial kedekatan manusia dengan lingkungan.
Menciptakan iklim demikian memang tidak secepat membayangkan menjadi seorang pegawai negeri atau pegawai swasta lain. Sebab, pegawai semacam itu mudah ditempuh apabila seseorang itu punya perwatakan dan syarat yang pas dengan instansi yang membutuhkan. Sehingga, kalau semua itu sudah lengkap, maka kemungkinan besar predikat pegawai itu akan tercapai.
Yang menyebabkan keinginan itu ditolak, karena masalah perwatakan seseorang itu, bisa mungkin kurang halus atau biasanya dengan masalah hello effek. Sehingga, wajar saja tak bisa menjadi personal dalam lembaga yang diinginkan. Lain halnya di pendidikan bahwa yang namanya konsep transformasi tidak memandang bahwa konsep itu harus sesuai dengan perwatakan seseorang, tetapi benar-benar mengacu pada wawasan multidimensional, sehingga mengesampingkan individu dan kepentingan non kemanusiaan.
Mungkin, ini suatu lelucon bahwa nama Saddam, pemimpin Iraq dimasukkan ke dalam pengertian pendidikan yang berkaitan dengan proses transformasi kelembagaan dan cara pandang para akademikus untuk menciptakan iklim kemanusiaan yang furistik-intelektual. Agaknya cocok bahwa figur Saddam yang kontroversial itu menjadi inspirator bukan heroator-sebagaimana tuntutan para ahli pendidikan untuk mengadakan perubahan besar-besaran.
Makna dari inspirator Saddam ini, mempunyai keberanian meski secara kultural harus melawan kebudayaan yang berkuasa dan berpengaruh di lingkungan tersebut. Sedang kelemahan kultur adalah terlalu takut melihat sistem tersebut. Selain itu, kelambanan cara befikir masih mendominasi, sehingga untuk menciptakan manuver-manuver baru golongan kita masih jauh tertinggal.
Karena itu, meski profil Saddam yang dalam Perang Teluk secara militer dengan kekuatan tentara multi-nasional yang merupakan koalisi dari 30 negara tetapi dalam masalah opini publik strategi politik untuk membangkitkan kemanusiaan manusia telah berhasil hasilnya masyarakat mengecam konsep yang terpola dalam kultur besar sedang berpengaruh dan berkuasa.
Komentar
Mungkin, ini akan menjadi barang baru, kalau di kampus muncul Saddam-Saddam yang bergerak menentang kultur-kultur klasik yang sudah tidak zaman lagi dipertahankan. Sehingga Bush-Bush dan Fadh-Fadh ala kampus akan hilang (bukan orangnya), tetapi wawasan perdukunannya tak mampu dikurikulumkan lagi.
Percakapan
Prediksi inspirator tentang Saddam untuk mengetahui mungkinkah gagasan dapat diwujudkan, baik secara cepat atau pelan-pelan adalah dilihat dari perkembangan percakapan kita masing-masing. Maksudnya bahwa isyu itu bisa muncul menjadi permasalahan umum. Dan secara politis, massa telah dikuasai oleh masalah tersebut.
Jika diprosentasekan, memang masyarakat kampus belum bisa dikuasai isyu umum, karena kuatnya birokrasi yang melakukan penyensoran terhadap informasi luar. Sehingga, para akademikus banyak yang tertinggal dengan jaringan-jaringan informasi. Bagi mereka yang tidak membaca, biasanya kekuatan ingatan tak bisa tahan lama, karena iklim memang belum mendukung.
Sebagai alternatif, para akademikus khususnya mahasiswanya, harus melakukan pendekatan dengan media massa. Sebab, melalui media ini kita kita akan lebih mudah menginformasikan gagasan-gagasan pembaharuan yang penting untuk kemanusiaan. Sehingga dalam pelan-pelan publik akan bisa dikuasai dan gemes dengan kultur yang tidak mengenal etik ilmiah dan etik kemanusiaan, yakni ke SKS-an dan kepaternalistikan. (Saf)
Mempunyai keberanian meski secara kultural harus melawan kebudayaan yang berkuasa dan berpengaruh di lingkungan tersebut.
Saddam